Indonesia telah dikenal sebagai negara yang multietnis dan multikultur. Meskipun sudah berada dalam ruang ‘modern state’ sejak para founding fathers menyatakan kemerdekaan terhadap kolonialisme Belanda di tahun 1945, namun residu dari situasi kolonial yaitu keberadaan kelompok masyarakat adat dengan semua problematika mereka dalam konteks Indonesia sebagai modern state hingga kini masih eksis. Hal ini diperlihatkan oleh peristiwa yang berlangsung dalam kurun triwulan pertama tahun 2009, ketika media baik cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus perseteruan antara dua Suku Anak Dalam yang mendiami Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi di Pengadilan Negeri Sorolangun Jambi. Kasus ini bermula ketika Tumenggung Celitai dan Tumenggung Mato Gunung dari Suku Anak Dalam Celitai terlibat bentrok dengan warga suku Anak Dalam Singosari pimpinan Temenggung Majid di pinggiran hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten Sorolangun 12 Desember 2008 silam. Bentrokan yang terjadi di Desa Pematang Kebau, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun ini mengakibatkan tewasnya tiga warga Suku Anak Dalam yakni Nunai (Celitai), Melenting Laman dan Besilang (Singosaren).
Bentrokan dipicu oleh persoalan pinjam meminjam chainsaw (alat pemotong kayu) dari Suku Anak Dalam pimpinan Tumenggung Celitai kepada Tumenggung Majid. Tumenggung Majid yang memimjam alat pemotong kayu dengan uang sewa sebesar Rp 800.000 ini kemudian meminjamkanya kepada pihak ketiga. Persoalan terjadi ketika alat ini mengalami kerusakan. Meskipun upaya adat telah dilakukan tetapi persoalan ini tetap bergulir menjadi bentrokan berdarah manakala kelompok Tumenggung Majid yang bertanggungjawab terhadap kerusakan mesin pemotong kayu tidak memenuhi janji untuk membayar ganti rugi berupa kain. Persoalan inipun kemudian coba diselesaikan melalui jalur hukum adat dengan kesepakatan satu nyawa dihargai 500 lembar kain. Dengan mendasarkan pada kesepakatan adat maka Tumenggung Celitai menyerahkan 1000 kain kepada Tumenggung Majid dan sebaliknya Tumenggung Majid membayar 500 kain kepada Tumenggung Celitai karena korban jatuh di pihak Tumenggung Celitai hanya satu orang.
Persoalan tidak berhenti sampai disini karena aparat hukum terlanjur memproses kasus ini ke jalur hukum. Dengan ditahannya dua orang Suku Anak Dalam ini muncul protes di banyak kalangan warga Suku Anak Dalam. Mereka menggelar tenda di halaman pengadilan negeri Sorolangun Jambi. Tidak jarang setiap kali proses hukum di pengadilan digelar, hakim dan polisi harus bersitegang dengan warga Suku Anak Dalam. Mereka tidak segan-segan melempari batu kepada aparat yang sedang bertugas. Meskipun protes telah dilayangkan oleh kelompok Tumenggung Celitai dan oleh enam Tumenggung pada Januari silam kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi dan Kepala Polri untuk meminta Celitai dan Mato Gunung dilepaskan tetapi proses hukum tetap dijalankan. Mereka berpendapat bahwa persoalan ini tidak perlu masuk dalam jalur hukum karena telah diselesaikan di tingkat adat.
Kasus ini sebenarnya hanya sekelumit kecil contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia. Manakala kasus perselisihan dan pertikaian yang melibatkan dua warga suku/masyarakat pedalaman coba diselesaikan di tingkat adat tetapi proses hukum negara (positif) tetap dijalankan. Dan kadang kala timbul persoalan manakala tidak ada ‘kesepahaman’ antara hukum adat dengan hukum positif milik negara. Negara sebagai pemangku kekuasaan merasa berhak melakukan pemaksaan terhadap dihormatinya hukum positif milik negara sehingga segala persoalan dan perselisihan yang terjadi di dalam area Negara Indonesia mau tidak mau harus diselesaikan dengan menggunakan hukum positif milik Negara Indonesia.
Padahal ketika Negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya atas dasar batas wilayah tertentu, di atas klaim tersebut telah hidup begitu banyak kesatuan masyarakat yang telah memiliki sistem nilai tradisional yang dipercaya, diyakini dan dipatuhi secara turun temurun untuk mengendalikan hidup mereka. Sistem nilai ini yang kemudian disebut dengan hukum adat karena hukum adat didasarkan pada norma kehidupan sehari-hari dan merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sehingga hukum menjadi tumbuh bersama masyarakat. Keberadaannya bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang dinaunginya.
Berbeda dengan hukum positif milik negara. Meskipun secara yuridis dia sah dan legal sebagai hukum positif karena telah memenuhi syarat-syarat perundang-undangan baik secara formal (ditetapkan oleh pihak yang berwenang) dan material (berlaku secara umum) tetapi sayangnya hukum positif kadang kala kurang bisa memenuhi harapan dan menjangkau semua hal karena sifatnya yang kaku, statis dan rigid. Sementara masyarakat yang dinaungi oleh hukum positif telah mengalami perubahan secara dinamis. Apalagi produk hukum positif milik negara adalah turunan dari berbagai produk hukum milik kolonial Belanda yang pada waktu itu dibentuk hanya sekedar untuk mengukuhkan kekuasaan atas tanah jajahan sehingga rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum cenderung diabaikan oleh hukum ini.
Untuk itulah sudah saatnya negara berani berpijak pada hukum buatan sendiri dan meninggalkan produk hukum warisan milik kolonial Belanda. Tidak selamanya hukum yang lahir dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tidak membawa manfaat bagi negara. Sebagai contoh dalam adat pengelolaan hutan di Aceh ada peraturan penebangan hutan yang harus berjarak beberapa meter dari bibir sungai. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi. Apabila nilai ini diadopsi dalam hukum positif tentulah kerusakan hutan yang sekarang terjadi di Aceh dapat diminalisir. Dan yang tidak kalah penting lagi dalam pembentukan hukum positif milik negara ini adalah adanya pemenuhan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta adanya pemenuhan syarat formal dalam proses pembentukannya. Jangan sampai hanya karena memenuhi rasa kepastian hukum semata dari pihak-pihak yang berkepentingan maka rasa keadilan dan kemanfaatan ditinggalkan. Tidak jarang produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang lewat proses legislasi Badan Perwakilan Rakyat merupakan cerminan ‘bisinis’ perundangan yang menguntungkan pihak tertentu saja. Diharapkan dengan berpijak pada hukum milik sendiri yang merupakan gambaran dari nilai-nilai yang selama ini diyakini dan dihormati bersama maka ‘ketidaksepahaman’ antara hukum adat dan negara yang selama ini sering terjadi di Indonesia akan dapat mencapai titik temu untuk dicarikan solusinya. (Septi Satriani)
Persoalan tidak berhenti sampai disini karena aparat hukum terlanjur memproses kasus ini ke jalur hukum. Dengan ditahannya dua orang Suku Anak Dalam ini muncul protes di banyak kalangan warga Suku Anak Dalam. Mereka menggelar tenda di halaman pengadilan negeri Sorolangun Jambi. Tidak jarang setiap kali proses hukum di pengadilan digelar, hakim dan polisi harus bersitegang dengan warga Suku Anak Dalam. Mereka tidak segan-segan melempari batu kepada aparat yang sedang bertugas. Meskipun protes telah dilayangkan oleh kelompok Tumenggung Celitai dan oleh enam Tumenggung pada Januari silam kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi dan Kepala Polri untuk meminta Celitai dan Mato Gunung dilepaskan tetapi proses hukum tetap dijalankan. Mereka berpendapat bahwa persoalan ini tidak perlu masuk dalam jalur hukum karena telah diselesaikan di tingkat adat.
Kasus ini sebenarnya hanya sekelumit kecil contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia. Manakala kasus perselisihan dan pertikaian yang melibatkan dua warga suku/masyarakat pedalaman coba diselesaikan di tingkat adat tetapi proses hukum negara (positif) tetap dijalankan. Dan kadang kala timbul persoalan manakala tidak ada ‘kesepahaman’ antara hukum adat dengan hukum positif milik negara. Negara sebagai pemangku kekuasaan merasa berhak melakukan pemaksaan terhadap dihormatinya hukum positif milik negara sehingga segala persoalan dan perselisihan yang terjadi di dalam area Negara Indonesia mau tidak mau harus diselesaikan dengan menggunakan hukum positif milik Negara Indonesia.
Padahal ketika Negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya atas dasar batas wilayah tertentu, di atas klaim tersebut telah hidup begitu banyak kesatuan masyarakat yang telah memiliki sistem nilai tradisional yang dipercaya, diyakini dan dipatuhi secara turun temurun untuk mengendalikan hidup mereka. Sistem nilai ini yang kemudian disebut dengan hukum adat karena hukum adat didasarkan pada norma kehidupan sehari-hari dan merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sehingga hukum menjadi tumbuh bersama masyarakat. Keberadaannya bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang dinaunginya.
Berbeda dengan hukum positif milik negara. Meskipun secara yuridis dia sah dan legal sebagai hukum positif karena telah memenuhi syarat-syarat perundang-undangan baik secara formal (ditetapkan oleh pihak yang berwenang) dan material (berlaku secara umum) tetapi sayangnya hukum positif kadang kala kurang bisa memenuhi harapan dan menjangkau semua hal karena sifatnya yang kaku, statis dan rigid. Sementara masyarakat yang dinaungi oleh hukum positif telah mengalami perubahan secara dinamis. Apalagi produk hukum positif milik negara adalah turunan dari berbagai produk hukum milik kolonial Belanda yang pada waktu itu dibentuk hanya sekedar untuk mengukuhkan kekuasaan atas tanah jajahan sehingga rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum cenderung diabaikan oleh hukum ini.
Untuk itulah sudah saatnya negara berani berpijak pada hukum buatan sendiri dan meninggalkan produk hukum warisan milik kolonial Belanda. Tidak selamanya hukum yang lahir dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tidak membawa manfaat bagi negara. Sebagai contoh dalam adat pengelolaan hutan di Aceh ada peraturan penebangan hutan yang harus berjarak beberapa meter dari bibir sungai. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi. Apabila nilai ini diadopsi dalam hukum positif tentulah kerusakan hutan yang sekarang terjadi di Aceh dapat diminalisir. Dan yang tidak kalah penting lagi dalam pembentukan hukum positif milik negara ini adalah adanya pemenuhan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta adanya pemenuhan syarat formal dalam proses pembentukannya. Jangan sampai hanya karena memenuhi rasa kepastian hukum semata dari pihak-pihak yang berkepentingan maka rasa keadilan dan kemanfaatan ditinggalkan. Tidak jarang produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang lewat proses legislasi Badan Perwakilan Rakyat merupakan cerminan ‘bisinis’ perundangan yang menguntungkan pihak tertentu saja. Diharapkan dengan berpijak pada hukum milik sendiri yang merupakan gambaran dari nilai-nilai yang selama ini diyakini dan dihormati bersama maka ‘ketidaksepahaman’ antara hukum adat dan negara yang selama ini sering terjadi di Indonesia akan dapat mencapai titik temu untuk dicarikan solusinya. (Septi Satriani)

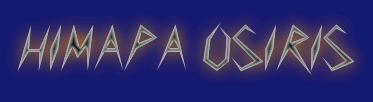
Tidak ada komentar:
Posting Komentar